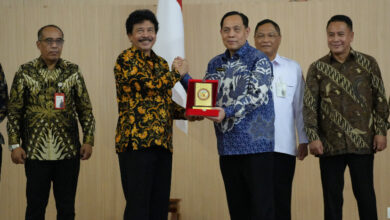Menyemai Nasionalisme Pemuda di Era Post-Truth

Oleh: Ahmad Kholikul Khoir*
Saat ini, kita sedang berada dalam suatu era dimana barometer kebenaran tak lagi terletak pada fakta objektif, namun pada tarikan emosi dan keyakinan subjektif. Sehingga, tidak sedikit kita temukan orang yang sharing suatu berita, tanpa melalui proses penyaringan. Alhasil, dengan mudah berita-berita bohong (hoax) bertebaran dimana-mana.
Berita bohong telah menjadi wabah penyakit yang merusak akal sehat dan moral manusia. Dimana penyintasnya tak lagi yang tak menikmati pendidikan struktural, namun juga pada kaum intelektual. Pasalnya, medsos kerapkali hanya menyajikan informasi yang dianggap relevan bagi penggunanya (algoritma). Sehingga dengan mudah terjadi miss-informasi, hingga disinformasi yang mengarah pada polarisasi.
Tidak sedikit ketegangan dan konflik sosial di Indonesia yang disulut oleh hoax media sosial. Salah satunya adalah kasus Front Pembela Islam (FPI) yang menyerang, bahkan membakar markas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI). Sehingga kerugian yang ditimbulkan mencapai ratusan juta rupiah (Okezone 28/03/2018).
Bagaimanapun, telah banyak upaya pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya dengan dibuatnya Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Sayangnya, upaya-upaya tersebut masih banyak yang bersifat kuratif. Padahal, akar permasalahanya terletak pada kodrat manusia yang harus dimanipulasi secara positif.
Untuk itu, elemen masyarakat harus turut serta dalam mengatasi masalah ini, terutama para kawula muda. Sebagaimana The Founding Fathers Ir. Soekarno mengatakan “Kalau pemuda sudah berumur 21-22 tahun sama sekali tidak berjuang, tak bercita-cita, tak bergiat untuk tanah air dan bangsa, pemuda begini baiknya digunduli saja kepalanya”. Hal ini menjadi pengingat bagi kita para pemuda agar memiliki semangat persatuan dalam mengatasi problematika bangsa: berita bohong (hoax).
Problematika Medsos
Sedihnya, tidak sedikit kawula muda yang telah terpapar paham radikal. Sebagaimana penelitian BIN (2017) mencatat, terdapat 24 persen mahasiswa dan 23,5 persen pelajar SMA yang menyetujui tegaknya negara islam di Indonesia. Padahal, radikalisme adalah salah satu hulu dari kemunduran, bahkan kehancuran suatu negara.
Banyak faktor yang menjadi pemantik munculnya radikalisme pada pemuda (millenial). Salah satunya adalah propaganda media sosial. Pasalnya, pemuda di era digital ini, untuk mencari informasi yang lebih luas selalu bergantung pada media tersebut. Padahal, tidak sedikit paham radikal hingga hoax yang masih tersebar luas di dalamnya. Tanpa disadari, aset emas negara ini, terpapar hoax dan paham tersebut.
Sungguh, tidak mudah dalam mengatasi problematika ini. Dimana radikalisme pemuda tak lagi terletak pada ranah kognitif, namun telah masuk pada ranah afektif. Pasalnya, media sosial mampu mempengaruhi sistem limbic otak yang berisi perasaan dan emosi, yang dapat menciptakan long term memory (ingatan jangka panjang). Untuk itu, harus ada upaya-upaya yang mampu mengembalikan akal sehat, sekaligus menumbuhkan emosi positif pada mereka.
Pelbagai Upaya
Ada beberapa upaya yang harus dilakukan agar para pemuda tidak terjangkiti radikalisme. Pertama, pendidikan sebaya (peer education). Tak bisa dimungkiri, pendidikan di tingkat Sekolah hingga Perguruan Tinggi telah mengajarkan nasionalisme. Akan tetapi, upaya ini tak banyak pengaruhnya dalam meminimalisir radikalisme. Pasalnya, mereka lebih mempercayai informasi yang diperoleh dari teman sebayanya. Untuk itu, perlu adanya teman sebayayang mampu menjadi penyalur informasi yang benar (peer educator).
Kedua, memperbanyak dialog kebangsaan di Perguruan Tinggi. Sebagaimana disampaikan Direktur Badan Nasional Pencegahan Terorisme (BNPT) bahwa salah satu pemantik masuknya radikalisme di lingkungan kampus, adalah kurangnya pemahaman mahasiswa terkait wawasan kebangsaan (Detik 29/06/2018). Oleh karena itu, kampus harus sesering mungkin mengadakan dialog-dialog kebangsaaan. Agar lembaga ini, tak menjelma menjadi sarang penghancur kebhinekaan.
Ketiga, mengadakan dialog lintas agama. Sebagaimana disampaikan BNPT, radikalisme mahasiswa juga dipicu oleh kurangnya pemahaman pada ajaran agama. Maka dialog lintas agama harus digalakkan. Namun, bukan dengan diskusi yang mempertontonkan kebenaran, dan kesalahan masing-masing agama. Pasalnya, kerapkali hal ini justru memicu kebencian dan konflik sosial. Dialog yang dimaksudkan adalah, dengan saling membuka pintu ke-sepemahaman dan inklusivitas agama. Harapanya, agar empathy dan emosi-emosi positif pemuda dapat dimunculkan.
Sungguh, tidak mudah menjadi pemuda di era disrupsi. Banyak tantangan yang harus dihadapi, mulai dari hoax, radikalisme dan lain-lain. Padahal, peran pemuda sangat dibutuhkan bagi negara, agar rencana-rencana pembangunan dan kemajuan dapat segera direalisasikan. Maka dari itu, upaya-upaya preventif terkait transmisi hoax harus dimaksimalkan. agar radikalisasi pemuda dapat terhindarkan.
*Penulis adalah Mahasiswa Prodi Psikologi Universitas Islam Indonesia, sekaligus Awardee Hafidz Quran UII.