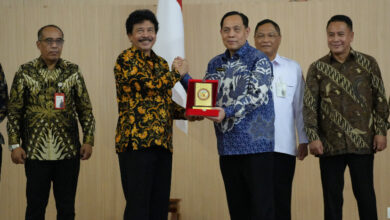Menakar Erat Peranan MUI

Oleh : Bagas Prasetyo )*
Menelaah langkah sekaligus tindakan kongkrit Pemerintah Presiden Jokowi terhadap kegaduhan yang terjadi di masyarakat akibat fatwa Majelis Ulama Indonesia atau yang disingkat dengan MUI, terkait larangan pemakaian atribut non Muslim. Pemerintah melalui Menko Polhukam Wiranto, menyatakan bahwa MUI harus melakukan koordinasi dengan Kemenag dan Polri sebelum mengeluarkan fatwa. Koordinasi antara Pemerintah dan MUI harus dilakukan “agar fatwa yang dikeluarkan bisa menghasilkan kebaikan dan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.”
Munculnya sikap Pemerintah ini tentu saja terkait dengan tindakan-tindakan sweeping di tempat publik seperti mall atau pertokoan yang pegawainya memakai atribut atau hiasan yang terkait dengan Natalan. Kapolri telah mengambil langakah disipliner kepada beberapa Kapolres yang ikut menyebarluaskan fatwa MUI itu. Selain itu, Kapolri juga memerintahkan seluruh jajarannya utk menindak setiap pelaku sweeping terhadap atribut Natalan.
Tindakan Pemerintah untuk meminta MUI berkoordinasi ini merupakan langkah maju, walupun harus tetap dilihat buktinya apakah setelah ini fatwa-fatwa produksi MUI masih akan menciptakan kegaduhan dan keresahan seperti saat ini. Polri yang dianggap telah tegas dalam mengemukakan bahwa fatwa MUI bukan hukum positif, juga merupakan sebuah progress. Dan ini akan lebih baik lagi jika fatwa-fatwa MUI tidak lagi digunakan sebagai satu-satunya sumber fatwa keagamaan (Islam) oleh aparat Pemerintah baik di pusat maupun daerah. Sebab jika MUI masih memiliki klaim monopoliostik seperti itu, niscaya kemungkian akan terulangnya pembuatan fatwa yang divisive seperti yang yang berkaitan dengan atribut non Muslim tersebut, akan terbuka.
Sejatinya yang lebih penting lagi adalah mendudukkan perkara status MUI dalam konstelasi relasi negara dan masyarakat sipil. MUI bukan lembaga negara atau kuasi negara, walaupun ia mendapat anggaran dari APBN/APBD. Oleh sebab itu banyak pihak yang serta merta menganggap MUI adalah pihak yang merepresentasikan otoritas negara dalam urusan keagamaan, bahkan kadang-kadang Kemenag pun tidak terlalu menunjukan sikap yang jelas ketika berhadapan dengan ormas yang satu ini. Padahal dibanding dengan ormas-ormas Islam besar seperti NU, Muhammadiyah, persis, Al-Washliyah, atau bahkan dengan LDII sekalipun, MUI tak punya basis massa.
Namun karena warisan kekuasaan rezim Orba yang masih berlanjut sampai Pemerintah pasca-Reformasi, maka MUI seakan-akan menjadi semacam lembaga negara. Bahkan sementara tokoh MUI menganggap seakan-akan MUI ini adalah perwakilan ummat Islam dan lembaga tertinggi Ulama di Indonesia! Padahal kapasitas keulamaan di dalam struktur MUI sendiri kini sering diragukan, menyusul sering munculnya fatwa-fatwa yang kontroversial serta keterkaitan mereka dengan kelompok kepentingan politik.
MUI tak perlu dibubarkan, tetapi organisasi ini perlu direformasi total sehingga kesan yang ada di ranah publik, seolah-olah mewakili aspirasi seluruh ummat dan ulama Islam, serta satu-satunya lembaga pembuat fatwa itu, tidak ada lagi. Kalaupun MUI membuat fatwa, tidak harus digunakan sebagai satu-satunya sumber pertimbangan atau rekomendasi dalam masalah keislaman, termasuk bidang hukum. Biarkan saja ormas-ormas Islam yang ada di negeri ini juga ikut berkontribusi terhadap wacana dan kiprah keagamaan. Kemenag tetap menjadi lembaga negara yang melakukan koordinasi hubungan antara mereka dan Pemerintah/Negara. Yang tak kalah penting dalam reformasi MUI adalah akuntabilitas keuangannya yang selama ini menjadi pertanyaan publik. Hanya dengan reformasi total seperti itu MUI akan menjadi bagian integral yang produktif dan mandiri bagi upaya pemberdayaan ummat Islam Indonesia dalam kerangka kebangsaan dan NKRI.
Bagaimanapun juga, kata “Indonesia” didalam singkatan MUI adalah sebuah penanda (signifier) yg paling utama. Apapun yang dilakukan MUI, harus tetap berlandaskan dan berorientasi kepada NKRI.
)* Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Brawijaya